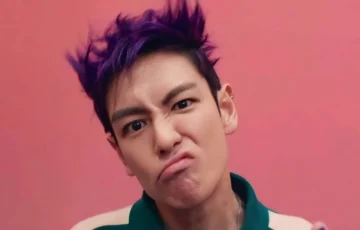The Crown adalah serial televisi drama sejarah tentang pemerintahan Elizabeth II yang merupakan Ratu dari Britania Raya dan wilayah Persemakmuran lainnya dari tahun 1952 hingga 2022. Serial ini lahir dari kreator Peter Morgan yang telah dinominasikan sebanyak 2 kali meraih piala Oscar untuk film The Queen (2007) dan Frost/Nixon (2009).
Empat musim pertama The Crown diterima dengan baik oleh para kritikus, dipuji karena nilai akting, penyutradaraan, penulisan, sinematografi, dan produksinya. Musim kelima menerima ulasan beragam hingga positif, dan musim keenam menerima ulasan beragam hingga negatif. Kritik terhadap ketidakakuratan sejarah serial ini juga menjadi salah satu sorotan selama musim keempat dan kelima.
The Crown telah menerima banyak penghargaan, termasuk total dua puluh satu penghargaan Primetime Emmy Award untuk empat musim pertamanya, termasuk predikat Outstanding Drama Series untuk musim keempat dan tujuh penghargaan untuk para pemerannya.
Bagian pertama dari musim keenam sebanyak 4 episode telah tayang di Netflix sejak 16 November 2023.
Review serial The Crown (2023)
Seberapa penting akurasi pada serial berdasar kisah nyata?

Tahun 2016, Netflix merilis serial The Crown yang mengupas kehidupan keluarga kerajaan Inggris. Siapa yang menyangka bahwa publik dan juga kritikus menyambutnya dengan meriah.
Tanggal 4 November 2016 akan menjadi tanggal yang selalu dikenang pecinta serial The Crown. 10 episode diluncurkan perdana sekaligus oleh Netflix dan kita melihat dengan lebih detil dari ruang tamu hingga ruang paling privat dari kehidupan Ratu Elizabeth II. Secara garis besar, musim pertama The Crown menelusuri kehidupan Ratu Elizabeth II dari pernikahannya pada tahun 1947. Lantas kita melihat bagaimana ia menjalankan perannya di awal masa pemerintahannya hingga tahun 1955.
Dalam rentang waktu ini terjadi sejumlah peristiwa penting seperti kematian Raja George VI yang mendorong naiknya Elizabeth ke tahta, yang berujung pada pada pengunduran diri Winston Churchill sebagai perdana menteri. Musim pertama The Crown juga mengisahkan soal saudara perempuan Elizabeth, Putri Margaret, yang memutuskan untuk tidak menikah dengan Peter Townsend.
Dengan berfokus pada sosok Ratu Elizabeth II mau tak mau kita pun memperhatikan aktris yang memerankannya yaitu Claire Foy. Sebelum terlibat di serial The Crown, bisa jadi kita hanya mengingat peran kecil yang dimainkannya di film The Lady in the Van (2015) bersama Maggie Smith.
Seiring dengan popularitas The Crown yang menanjak, juga kualitasnya yang cemerlang, Claire akhirnya mendapatkan perhatian dari berbagai penghargaan bergengsi. Ia membawa pulang piala Golden Globe sekaligus Screen Actors Guild di tahun 2017 dan meraih piala Primetime Emmy Awards di tahun 2018.
Kritikus juga beramai-ramai memberi pujian setinggi langit untuk The Crown. The Atlantic menulis, “penggambaran pribadi dan kompleks tentang seorang raja yang menurut pengakuannya sendiri dalam serial itu lebih suka menjalani kehidupan lain yang sudah cukup memukau baginya.
Tapi The Crown juga merupakan pelajaran sejarah meskipun bersifat selektif. Serial ini dipotret dengan indah, dengan kreasi ulang yang sempurna dari segala sesuatu dari Ruang Tahta di Buckingham.” The Telegraph menobatkan The Crown sebagai “serial terbaik di televisi.”
Dari sini, Entertainment Weekly memujinya sebagai “kreasi Peter Morgan bekerja dengan sangat baik secara keseluruhan karena secara konsisten ditulis dengan baik dan difilmkan dengan baik dan kekuatan terbesarnya sekali lagi ada pada kastingnya.”
Meskipun sejak awal penayangannya, nada-nada sumbang terkait dengan akurasi juga mulai bermunculan namun The Crown musim perdana meluncur nyaris tanpa masalah. Menurut perkiraan The Guardian, soal akurasi mungkin tidak menjadi prioritas untuk menjadi sorotan karena yang disajikan adalah kisah yang terentang berpuluh tahun silam (tahun 1947-1955) di mana sebagian besar kritikus, jurnalis hingga kebanyakan penonton televisi tak punya gambaran apapun tentang apa yang terjadi pada tahun-tahun tersebut.
Namun setelah musim kedua dan terus berlanjut hingga musim keenam bagian pertama yang baru saja tayang pada 16 November 2023, akurasi antara apa yang sesungguhnya betul-betul terjadi pada keluarga kerajaan dengan apa yang digambarkan dalam episode demi episode serialnya perlahan menjadi krusial. Begitupun pertanyaan paling penting sesungguhnya adalah perlukah akurasi mendekati kisah aslinya pada film/serial/miniseri atau sineas hanya perlu bertanggung jawab pada kualitas produk dan menghalalkan dramatisasi dengan cara apapun?
Menguliti Kingdom of Heaven hingga Green Book

Tahun 2005 Ridley Scott merilis film epik sejarah berjudul Kingdom of Heaven. Film yang berfokus pada kisah seputar jatuhnya Yerusalem ke tangan Sultan Saladin di tahun 1187 itu dibintangi oleh Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, Edward Norton, Liam Neeson dan Michael Sheen.
Dengan penampilan para aktor yang magnetik, adegan peperangan kolosal yang memukau hingga visual yang memang selalu disajikan Ridley dengan luar biasa beroleh hasil menakjubkan. Kingdom of Heaven meraup lebih dari 211 juta USD dan beroleh pujian dari kritikus diantaranya Rolling Stone yang menyebut film tersebut sebagai “hiburan yang meriah dari Ridley Scott”.
Tapi tak semua orang bertepuk tangan dengan pencapaian dari Kingdom of Heaven. Sejarawan dari Cambridge, Jonathan Riley-Smith, menyebut film tersebut sebagai “omong kosong” dan “sejarah versi Osama bin Laden”.
Sementara itu penulis sekaligus sejarawan asal Inggris, Michael Haag, menulis bahwa “Ridley Scott merevisi sejarah secara menyeluruh, atau lebih tepatnya mengada-ada.” Ia mengakhiri tinjauannya dengan menyatakan bahwa “tidak ada sesuatu pun yang banyak berhubungan dari film itu dengan fakta sejarah”.
Bahkan film sekelas Green Book yang menjadi Film Terbaik di ajang Academy Awards tahun 2019 juga mendapat kecaman karena digambarkan tak akurat. Green Book berfokus pada kisah virtuoso piano Afrika-Amerika, Donald Shirley dan supirnya yang berdarah Italia-Amerika, Tony Vallelonga saat mereka melakukan tur ke pedalaman Selatan pada tahun 1962.
Sepanjang perjalanan, Donald ditolak tampil di berbagai tempat, tak diperbolehkan duduk di restoran dan diserang secara fisik. Pada awalnya Tony, sebagaimana kebanyakan orang dari kaumnya saat itu, juga memusuhi orang kulit hitam.
Ketika ia mengenal Donald, rasa keadilan dari dalam dirinya muncul mengalahkan prasangkanya. Pada saat yang sama, Donald sejak awal digambarkan sebagai orang sombong yang tegang dan bersikap manis, dan justru tidak berhubungan dengan komunitas Afrika-Amerika. Dipaksa menghabiskan waktu dengan Tony dalam situasi yang unik, keduanya akhirnya terbuka dan saling menerima satu sama lain. Dalam adegan klimaks, Tony mendorong Donald untuk makan ayam goreng untuk pertama kalinya dengan menggunakan tangan kosong.
Ketika akhirnya beredar secara luas terlebih setelah memboyong 3 piala Oscar tak membuat gentar pihak keluarga Donald untuk mengkritik Green Book yang sakit hati dengan ketidakakuratan yang digambarkan dalam film tersebut. Dari pihak keluarga Donald menyerang film tersebut dan menyebut secara gamblang bahwa tak pernah ada persahabatan erat antara Donald dan Tony dalam kehidupan nyata sebagaimana yang digambarkan di film.
Salah satu saudara laki-laki Donald menyebut Green Book sebagai “simfoni kebohongan”. The Guardian sendiri menganggap bahwa fiksionalisasi dalam film yang disutradarai Peter Farrelly tersebut tak sekedar demi alasan artistik namun juga terkait kepentingan representasi di Hollywood.
Dalam bukunya yang terbit tahun 2007, History Goes to the Movies: Studying History on Film, pakar film Marnie Hughes-Warrington menceritakan rasa frustrasi sejarawan Natalie Zemon Davies dalam mencoba bekerja dengan pembuat film. Berkolaborasi dengan sutradara film sejarah, Le Retour de Martin Guerre, Daniel Vigne dan Jean Claude Carriére, Natalie mengeluh bahwa “aspek cerita dikompresi, diubah atau bahkan ditinggalkan”. Sebagaimana dikutip dari The Guardian, Davies sempat “bertanya-tanya apakah film mampu menangani dan menyampaikan ‘ketidakpastian’, ‘yang mungkin’, ‘yang mungkin terjadi’.
Akurasi penggambaran kehidupan Putri Diana

Dalam empat episode dari musim keenam bagian pertama The Crown, kreator Peter Morgan memutuskan untuk berfokus pada kisah hidup Putri Diana. Kita dibawa untuk melihat kehidupan Putri Diana pasca-perceraian mulai dari perannya sebagai ibu yang penyayang bagi Pangeran William dan Harry, pekerjaan amalnya terkait soal ranjau darat di Bosnia, juga persahabatannya dengan pengusaha Mesir, Mohamed Al Fayed, dan tentu saja percintaannya dengan anak dari pengusaha tersebut, Dodi.
Dan juga yang paling ditunggu penonton adalah pada penggambaran peristiwa menjelang kematian Putri Diana yang berpuncak pada kecelakaan mobil yang menewaskannya bersama Dodi di jalan bawah tanah Pont de l’Alma di Paris.
Berbeda dengan musim pertama yang berlatar peristiwa yang terjadi lebih dari 40 tahun lalu, kematian Putri Diana yang “baru” berusia 26 tahun dianggap masih segar di ingatan sebagian besar penonton The Crown. Maka wajar saja jika penonton maupun sejarawan lebih banyak mencermati episode demi episode dibanding musim-musim sebelumnya.
Dalam sebuah adegan yang mendramatisasi percakapan Pangeran Charles dengan Ratu Elizabeth, Charles ditampakkan mendesak agar pesawat kerajaan membawa kembali peti mati Putri Diana dari Paris, serta meminta ibunya untuk berpidato di depan bangsa setelah ia mengungkapkan keraguannya.
“Saya akan menganggap (adegan) itu sebagai fiksi,” kata akademisi sekaligus ahli keluarga kerajaan, Pauline MacLaren. “Orang-orang tahu bahwa serial ini bukanlah sebuah film dokumenter dan saya pikir hal itu telah diketahui semua orang,” tambahnya sebagaimana dikutip dari BBC.

Dalam memoarnya yang terbit tahun ini berjudul Spare, Pangeran Harry menulis bahwa “Ayah tidak memelukku” ketika Pangeran Charles memberi tahunya ibunya telah meninggal dan bahwa tepukan di lutut adalah penghiburan terbesar yang dia terima. Dalam memoar tersebut, Pangeran Harry juga mengatakan ia tidak menangis sampai ia melihat peti mati ibunya diturunkan ke tanah, berbeda dari yang digambarkan dalam serialnya.
Begitupun sebagai kreator, Peter Morgan yang telah 2 kali dinominasikan meraih piala Oscar sudah memahami konsekuensi dari serial yang berjalan di wilayah abu-abu antara sejarah dan fiksi. “Semua kritik datang untuk mengantisipasi penayangan serial tersebut. Begitu keluar dan orang-orang menontonnya, mereka langsung terdiam. Dan mungkin merasa agak bodoh.”
***
Meskipun film/serial/miniseri punya keterbatasan dalam “mengapresiasi” akurasi secara banal namun sejumlah pihak juga menganggap bahwa film punya daya jangkau luar biasa besar yang tak dipunyai medium lain. Salah satunya dituturkan pakar abad pertengahan dan pakar film Amerika, A. Keith Kelly. “Apa yang belum mampu dicapai oleh tulisan selama berabad-abad dalam mengapresiasi peperangan abad pertengahan, dapat dicapai oleh film-film seperti Braveheart dan Henry V karya Branagh dalam hitungan menit.”