Tornado mengepung di sekitar Badan Sensor Film pada pertengahan tahun 1989. Tornado itu berupa teriakan hingga kecaman dari masyarakat hingga media sosial seputar film Pembalasan Ratu Laut Selatan (1988). Banyak yang tak terima mengapa film yang secara terang-terangan mempertontonkan payudara Yurike Prastika secara frontal dan menunjukkan siluet kemaluannya itu bisa lolos sensor.
Sebagian mencaci maki, sebagian melakukannya sembari bersyukur sudah menontonnya terlebih dahulu di bioskop dan sebagian lagi sadar bahwa film tersebut seharusnya ditarik dari bioskop bukan karena adegan vulgarnya tapi karena Pembalasan Ratu Laut Selatan adalah film yang “mahabodoh”.
Dalam Catatan Pinggir yang diterbitkan majalah Tempo pada 15 Juli 1989, Goenawan Mohamad menilai bahwa penyelesaian atas masalah soal film tersebut “bukanlah mengasah gunting sensor lebih tajam. Sensor adalah sebuah institusi yang sebenarnya tak punya hak untuk mengatakan bahwa dialah yang paling kompeten memutuskan apa yang baik dilihat dan tak baik dilihat orang banyak di Indonesia.”
Tiga puluh tahun berselang, sekali lagi tornado meraung-raung di sekitar Lembaga Sensor Film. Kali ini “korbannya” adalah film Hellboy (2019). Di negerinya sendiri, film yang menampilkan David Harbour sebagai sang antihero itu sesungguhnya sadar diri dengan bejibunnya adegan kekerasan yang melingkupinya sehingga tak bermasalah dengan kriteria usia penonton 21 tahun ke atas.
Namun entah kenapa ketika beredar di bioskop tanah air, Hellboy memilih menurunkan ratingnya ke usia penonton 17 tahun ke atas. Tentu saja aksi ini menimbulkan korban berupa pemotongan adegan yang cukup banyak dan mengganggu kenyamanan penonton. Lagi-lagi Lembaga Sensor Film menjadi sasaran amukan masyarakat.
Seberapa darurat sensor di layanan streaming?
Sineas versus LSF
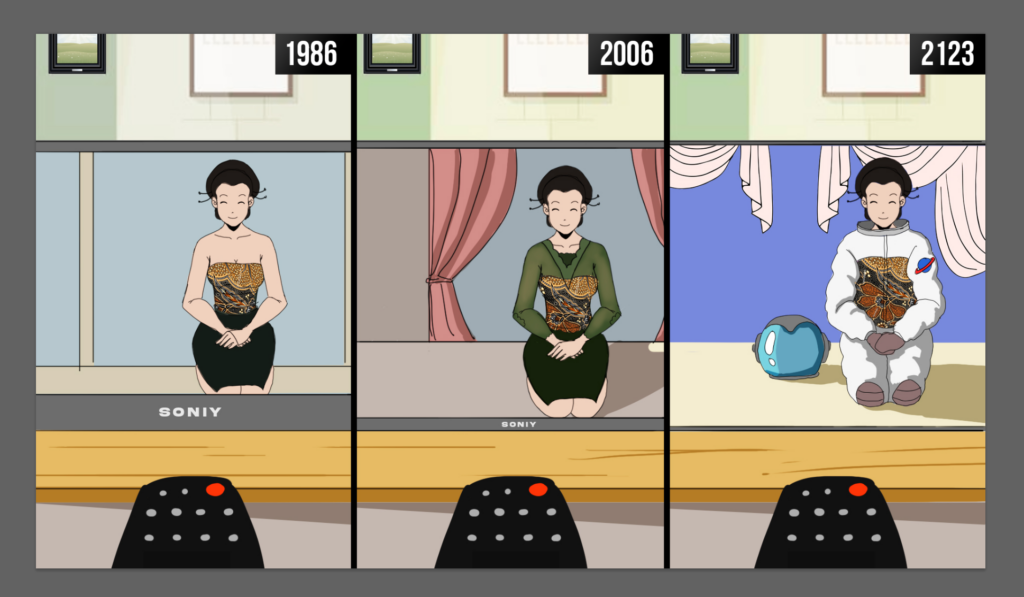
Dalam sejarahnya yang panjang, sineas dan Lembaga Sensor Film pun sering berada di kutub berseberangan. Sewaktu saya mewawancarai sutradara kampiun, Riri Riza, untuk Playboy Interview yang terbit di majalah Playboy Indonesia edisi November 2006, Riri juga menyebut bahwa ia sering emosi soal sensor.
“Menurut saya, yang namanya Lembaga Sensor Film di Indonesia, kalau kita pikirkan dan coba analisa, selalu membuat kita emosional. Siapapun pembuat film, wajar sekali jika berpikir seperti itu. Karenanya, kita berada dalam kondisi masih sangat terancam lembaga sensor.”
Nyaris senada dengan Riri, sutradara Joko Anwar juga sempat mengungkapkan kekhawatirannya yang dikutip dari CNN Indonesia terbitan 18 Maret 2016. “Keberadaan sensor dalam suatu negara bukan lagi cuma masalah pengekangan kreativitas. Tapi yang lebih penting sensor film juga menghambat kematangan masyarakat untuk menghadapi era informasi.”
Joko juga menilai Lembaga Sensor Film perlu lebih adaptif mengantisipasi era digital. “Saat ini dan ke depan, informasi tentang dan dalam bentuk apa pun, termasuk audio visual, tak akan dapat dibendung aksesnya. Masyarakat membutuhkan kemampuan untuk bisa menyaring [konten] yang bisa mereka terima. Kalau kontrol [sensor film] dipegang oleh negara, masyarakat tidak akan pernah menjadi masyarakat madani. Ini sangat berbahaya karena negara tidak akan sanggup menyaring semua informasi.”
Sensor tak melulu soal kekerasan dan seks

Gunting sensor memang kerap kali bahkan terlampau tajam bahkan untuk konten yang tak memuat adegan kekerasan maupun seks yang vulgar. Film dokumenter, Prison and Paradise (2010), dinyatakan tak lolos sensor karena dianggap potensial memberi pengaruh negatif terhadap generasi muda karena banyaknya dialog berbau propaganda di dalamnya yang dianggap bisa menyesatkan penonton.
Dalam film yang disutradarai Daniel Rudi Haryanto tersebut menampilkan wawancara para pelaku Bom Bali 2004 seperti Amrozi, Imam Samudra serta Mukhlas. Dalam film ini, para pelaku Bom Bali tersebut menyatakan dengan terang-terangan mengenai jihad dalam agama Islam dan pengeboman.
Alasan penolakan pemberian Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) oleh LSF tertuang lebih jelas dalam surat penolakan LSF No: 26/DVD/TLK/LSF.XII/2011 tertanggal 9 Desember 2011. “Film tersebut sarat dengan dialog-dialog propaganda yang menyesatkan, sehingga memberi pengaruh negatif terhadap generasi muda Islam Indonesia. Oleh karena itu film dokudrama ini tidak sesuai dengan kriteria penyensoran dan aspek keagamaan sehingga tidak dapat beredar atau diedarkan di wilayah R.I.”
“Aspek keagamaan” yang dimaksud dalam surat penolakan tersebut mengacu pada aturan sensor yang dibuat pada masa Orde Baru yaitu PP No.6 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film. Terkait aspek keagamaan yang dimaksud, sebuah film bisa ditolak sepenuhnya untuk diputar di wilayah hukum Indonesia dengan alasan-alasan keagamaan sebagai berikut:
(2) Unsur-unsur yang dinilai dari segi keagamaan, adalah:
- Yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dalam segala bentuk dan manifestasinya;
- Yang dapat merusak kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia; atau;
- Yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia.
Sejarah Lembaga Sensor Film di Indonesia

Dalam laman resmi lsf.go.id disebutkan bahwa Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 46/SK/M tahun 1965 mengatur bahwa penyelenggaraan sensor film dilakukan oleh lembaga bernama Badan Sensor Film. Badan Sensor Film mewajibkan seluruh bentuk program harus memiliki Surat Tanda Lulus Sensor terlebih dulu.
Pada tahun 1968, Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 44/SK/M/1968 menetapkan bahwa Badan Sensor Film berkedudukan di Jakarta dan bersifat nasional, beranggotakan 25 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Dalam perkembangannya, Badan Sensor Film kemudian berubah namanya menjadi Lembaga Sensor Film pada tahun 1992. Disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.
Pada tahun 1999, ketika Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, pemerintah menempatkan LSF ke dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Lalu pada tahun 2000, Lembaga Sensor Film dipindahkan ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Sampai kemudian pada tahun 2005, status Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan pada 2009, berubah lagi menjadi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), LSF tetap berada di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada 2009 itu lahirlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.
Pasca-reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu pada 11 Oktober 2011, Kemenbudpar, tempat selama ini LSF bernaung, berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Bidang Kebudayaan dipindahkan ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang kemudian berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/307.1/M.PAN-RB/01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada 27 Januari 2012, dengan resmi LSF berada di bawah Kemendikbud.
LSF beradaptasi dengan era digital
Menanggapi era digitalisasi yang tak bisa dibendung lagi, Lembaga Sensor Film pun berbenah. Fungsi gunting sensor yang terlampau tajam selama berpuluh tahun lantas beralih fungsi menjadi skema klasifikasi. Sebagaimana dimuat Kincir pada edisi 14 April 2019 terkait heboh sensor film Hellboy dijelaskan bagaimana alur tentang apa yang terjadi sejak film didaftarkan di Lembaga Sensor Film hingga kelak beroleh Surat Tanda Lulus Sensor Film. Pemilik mendaftarkan filmnya ke LSF.
Setelahnya film diteliti, dinilai, ditentukan kelayakannya, dan dilabeli dengan surat tanda lulus sensor (STLS) atau tidak lulus sensor. Jika tidak lulus, film dikembalikan kepada pemilik untuk diperbaiki. Jika sudah diperbaiki, film dapat diajukan lagi untuk diteliti dan dinilai kembali oleh LSF.
Dalam hal ini LSF hanya memberi catatan revisi, bukan memotongnya. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kelompok penyensor, film diteruskan ke sidang pleno untuk mendapatkan keputusan. Sesuai dengan amanat UU Perfilman 2009, LSF juga membuka ruang konsultasi prasensor bagi kreator yang ingin mendiskusikan filmnya untuk meminimalisir catatan sensor. Film dalam dan luar negeri yang bisa didaftarkan di LSF harus sudah terdaftar di Pusat Pengembangan Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pusbang Kemendikbud).
Saya sendiri mengalami apa yang terjadi dengan Lembaga Sensor Film yang mencoba terus beradaptasi. Ketika didaftarkan di LSF, film yang saya produseri berjudul Hijabers in Love [2014] lolos untuk usia 17 tahun ke atas. Tentu saja saya keberatan dengan rating tersebut dan membuka jalur komunikasi dengan LSF.
Terbukalah fakta salah atu adegan di kafe yang dikelola seorang ustadz memperlihatkan pelayan perempuan dengan busana berpotongan terbuka. Ketika melayani seorang tamu, busana tersebut tertarik ke atas dan memperlihatkan sedikit bagian perut dari pelayan. Daripada memotong adegan yang saya anggap menjadi bagian penting dari film, saya memilih untuk mengaburkan “bagian perut dari pelayan” tersebut. Dan hasilnya Hijabers in Love lolos sensor untuk usia 13 tahun ke atas.
Seberapa darurat sensor di layanan streaming?

Ketika bioskop dan televisi tak lagi memonopoli menjadi sumber hiburan dengan hadirnya penyedia layanan streaming (Over The Top/OTT) maka sejumlah pihak pun menilai sudah saatnya sensor juga mulai merambah ke sana. Menurut Bettina Cevenagh, Presiden Direktur Clarity Research Indonesia, perkembangan layanan streaming di Indonesia telah dimulai sejak 2013. Pasar pun makin ramai dengan kedatangan Netflix, Viu, Hooq, Catchplay, iFlix, dan Tribe pada 2016.
Lalu menjadi semakin membesar sejak seluruh dunia dilanda gelombang pandemi pada tahun 2020. Survei The Trade Desk melaporkan bahwa terdapat lebih dari 50 juta penonton di Indonesia yang mulai bergantung kepada layanan streaming atau tumbuh sekitar 25% dari tahun sebelumnya. Sementara itu dari data yang dirilis JustWatch pada akhir 2022 dilaporkan Disney+ Hotstar mendominasi pasar OTT di Tanah Air dengan persentase pangsa pasar (market share) mencapai 23%. Kemudian, pangsa pasar sisanya dikuasai oleh Netflix (21%), iflix (15%), Viu (12%), Vidio (10%), Prime Video (9%), HBO GO (7%), dan lainnya (3%).
Gejala merambahnya ke sensor ke layanan streaming sesungguhnya sudah dimulai sejak 2 tahun lalu. Tepatnya ketika dua stasiun televisi di bawah MNC Group, RCTi dan iNews, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi yang meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet juga bisa diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Uji materi tersebut lantas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi per Januari 2021 dengan sejumlah catatan: Pertama, OTT memang bukan penyiaran, karena OTT bersifat private dan eksklusif beda dengan Penyiaran yang disiarkan secara umum. Kedua, penyiaran disiarkan secara serentak dan bersamaan tergantung masyarakat untuk menonton berbeda dengan OTT, di mana hak sepenuhnya ada di masyarakat.
Ketiga, OTT sudah diatur dalam UU ITE, di mana Kominfo diberi kewenangan untuk mengatur termasuk memblokir juga UU Telekomunikasi jika terkait dengan penyedia jaringan. Keempat, OTT bagian dari ruang siber yang tidak berbatas teritori, beda dengan Penyiaran. Kelima, jika dipandang perlu pengaturan lebih komprehensif untuk OTT maka itu adalah sepenuhnya kewenangan pembentuk UU.
Sekitar 2,5 tahun setelahnya, gejala itu semakin terlihat. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Sturman Panjaitan mengeluhkan banyaknya konten yang berbau pornografi di layanan TV berlangganan. “Karena TV berlangganan ini kan banyak sekali porno-porno. Pornografi itu kan masih banyak sekali.
Selama ini apa yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia [KPI] ini? Karena kan tugas dan kewenangannya sudah jelas,” katanya sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, sendiri sedang mengkaji serius soal potensi memasukkan layanan streaming film seperti Netflix ke dalam ranah penyiaran seperti siaran TV konvensional. “Kita sedang mengkaji secara serius apakah nanti OTT (over the top, penyedia layanan video internet, red) dimasukkan dalam ranah penyiaran,” ujarnya pada Agustus lalu.
Gerakan sensor mandiri

Menarik memang mencermati betapa kegelisahan anggota DPR RI tersebut justru seperti berseberangan dengan apa yang dilakukan Lembaga Sensor Film selama ini terkait budaya sensor mandiri. LSF melihat dengan semakin tak terbendungnya konten digital. Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri yang telah dicanangkan pada penghujung tahun 2021 lalu semakin digencarkan oleh LSF. Dalam Pasal 61 UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman disebutkan bahwa Lembaga Sensor Film membantu masyarakat agar dapat memilah dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film.
Sesungguhnya gerakan sensor mandiri sudah diadaptasi oleh sineas/produser film setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Salah satu produser terkemuka, Manoj Punjabi, dari MD Entertainment, menanggapi hal tersebut ketika meluncurkan serial Kupu-Kupu Malam di layanan streaming WeTV. Serial yang dibintangi Michelle Ziudith menampilkan banyak adegan dewasa dan sejak awal pihak Manoj sudah tahu betul bahwa rating yang akan mereka terapkan adalah rating dewasa.
Dalam konferensi pers yang digelar di MD Place Jakarta, pada Minggu 13 November 2022, Manoj bahwa rating Kupu-Kupu Malam yang tayang di WeTV dan iFlix adalah khusus dewasa. “Ratingnya sudah pasti dewasa karena setiap episode bisa ada rating yang beda. Pastilah, trailer sudah begini, sangat dewasa. saya sekarang, kan (menerapkan) sensor mandiri. Jadi kami juga harus be alert, “ ujarnya sebagaimana dikutip dari Liputan 6. Produser film terlaris Indonesia sepanjang masa, KKN di Desa Penari, itu menekankan betul soal sensor mandiri ini. “Jadi benar-benar sensor mandiri penting. Ada aturan mainnya, saya harap masyarakat bertanggung jawab kepada anaknya atau siapa yang menonton harus sesuai umur.”
Belajar dari India
Sebenarnya kita bisa belajar dari India yang sudah mengalami apa yang akan kita alami saat ini sejak 3 tahun silam. Saat itu sejumlah layanan streaming yang beroperasi di India seperti Disney Plus dan Netflix terancam dikenakan sensor demi memenuhi permintaan pemerintah. Demi menjamin kebebasan artistik dari konten yang ada di layanan streaming, Netflix, Prime Video, Disney Plus dan 12 penyedia layanan streaming lainnya akhirnya menandatangani kesepakatan perjanjian sensor mandiri.
Dikutip dari Endgadget, sensor mandiri tersebut termasuk pendekatan umum untuk memberi label usia dan deskripsi konten serta cara melapor jika terjadi pelanggaran. Dalam kesepakatan perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa layanan streaming harus membentuk departemen pengaduan, komisi internal atau keduanya untuk menangani masalah terkait hal ini.
Saat ini pun kita sebagai penonton sudah bisa melakukan pembatasan konten secara mandiri melalui fitur khusus Kids Safe seperti yang diterapkan oleh Disney Plus sejak tahun 2020. Fitur ini ditujukan untuk menyaring konten yang layak untuk disaksikan oleh penonton anak-anak. Fitur serupa sesungguhnya juga sudah diterapkan oleh Netflix melalui fitur bernama Parental Control. Selain itu Netflix pun membuat profil akun untuk anak yang berisi konten-konten khusus film dan serial untuk penonton di bawah umur legal.
Karenanya masih perlukah sensor diberlakukan di layanan streaming saat ini?













