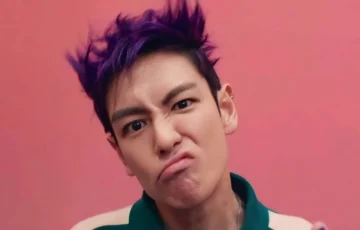The Buccaneers adalah serial drama yang dibuat oleh Katherine Jakeways berdasarkan novel berjudul sama yang merupakan karya terakhir dari penulis Amerika peraih Pulitzer, Edith Wharton. Novel ini diterbitkan setelah kematian Edith di tahun 1938.
The Buccaneers bercerita tentang kedatangan sekelompok gadis Amerika ke dalam masyarakat London pada tahun 1870-an dan mengakibatkan benturan budaya dengan dua pendekatan berbeda terhadap tradisi. Sebelumnya novel The Buccaneers diadaptasi untuk BBC Television sebagai miniseri pada tahun 1995.
The Buccaneers dibintangi para pemeran yang segar, cantik dan ganteng. Diantara mereka adalah Kristine Froseth (Looking For Alaska), Alisha Boe (13 Reasons Why), Josie Totah (serial ulang buat Saved by the Bell) dan pendatang baru, Guy Remmers dan Matthew Broome.
Kini The Buccaneers mewujud sebagai serial 8 episode yang tayang di Apple TV mulai 8 November 2023.
Review Serial The Buccaneers (2023)
Martin Scorsese, Edith Wharton dan adaptasi serampangan novel cemerlang

Tahun 1993. Setelah merilis 2 judul film yang dipenuhi adegan kekerasan, Raging Bull (1980) dan Goodfellas (1990), sutradara Martin Scorsese mengagetkan publik dengan The Age of Innocence.
Pada awalnya penulis Jay Cocks memberikan novel dari Edith Wharton tersebut kepada Martin sekitar tahun 1980. “Kalau suatu saat kamu ingin mengerjakan karya romantik, novel ini adalah pilihan tepat, “ ujarnya. Martin butuh hingga 10 tahun untuk mengadaptasi novel tersebut.
The Age of Innocence bukan novel sembarangan. Edith beroleh Pulitzer atas karyanya tersebut di tahun 1921 dan menjadi perempuan pertama yang menggondol penghargaan prestisius tersebut. Dalam autobiografinya, Edith menulis tentang The Age of Innocence bahwa hal itu mengizinkannya untuk menemukan “pelarian sesaat dengan mengingat kembali kenangan masa kanak-kanak saya tentang Amerika yang telah lama menghilang… semakin jelas bahwa dunia tempat saya dibesarkan dan dibentuk telah dihancurkan pada tahun 1914.”
Meskipun novel ini mempertanyakan asumsi dan moral masyarakat New York pada tahun 1870-an, novel ini tidak pernah berkembang menjadi kecaman langsung terhadap institusi tersebut. Novel ini terkenal karena perhatian Edith terhadap detail dan penggambaran akuratnya tentang bagaimana kehidupan kelas atas Amerika di Pantai Timur abad ke-19 serta tragedi sosial dalam plotnya. Namun di tangan Martin, The Age of Innocence menjadi sebuah karya yang membongkar kemunafikan masyarakat kelas atas di New York pada abad ke-19.
Kritikus merayakan visi yang menarik dari Martin atas adaptasinya tersebut. Kritikus terkenal Roger Ebert menulis, “kisah yang diceritakan di sini brutal dan penuh darah, kisah tentang hasrat seorang pria yang hancur, tentang hatinya yang hancur.
Ada lebih dari itu, dan adegan terakhir film ini, yang menyatukan semuanya, hampir tak tertahankan.” Rita Kempley dari The Washington Post menulis, “mungkin tidak terlalu mengejutkan bahwa Martin cekatan dalam mengeksplorasi nuansa perilaku Edwardian seperti menjadikan dirinya semacam representasi hukum kejantanan modern.”
Edith Wharton dan masyarakat New York

Sepanjang hidupnya tak kurang dari 15 novel dipublikasikan oleh Edith. Dan ia banyak menulis kisah tentang masyarakat kelas atas New York pada abad ke-19. Bisa jadi tak ada yang lebih pantas menuliskannya dengan gamblang, menarik dan penuh detail sebagaimana yang dilihat dan dijalaninya selain Edith. Pengamatannya atas masyarakat New York tersebut dituangkannya dalam beberapa novelnya diantaranya The House of Mirth, The Age of Innocence dan tentu saja novel terakhirnya, The Buccaneers.
Edith dengan jeli melihat dunia lama dan dunia baru yang saling bersinggungan dan bagaimana dunia baru dengan cepat mengubur dunia lama. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat sebuah fenomena tatkala gadis-gadis Amerika dari keluarga kaya raya (umumnya tidak diterima dalam masyarakat lama New York) menikah dengan bangsawan Inggris (sebagian besar mengalami kehancuran finansial setelah Amerika mulai menanam gandum di tanah mereka sendiri daripada mengimpor gandum dari Inggris).
Pada dasarnya ini adalah pertukaran hak milik dengan mahar yang besar. Para perempuan ini kelak akan terus mempengaruhi kepemimpinan negara. Putri Diana, misalnya, adalah keturunan pewaris saham dari pengusaha kereta api Amerika, Frances Ellen Work, yang menikah dengan bangsawan Inggris, Baron Fermoy.
Sebagaimana ditulis oleh Vogue, fenomena ini begitu lazim pada akhir abad ke-19, bahkan ada sebuah publikasi berjudul Titled American yang mencantumkan wanita dan gelar yang baru mereka peroleh, serta para bujangan Inggris yang memenuhi syarat serta kekayaan dan pendapatan mereka.
Gadis bebas Amerika bertemu bangsawan Inggris yang kaku

Dalam 3 episode awal yang sudah tayang di Apple TV, kita melihat bagaimana novel The Buccaneers diadaptasi secara serampangan oleh kreator Katherine Jakeways. Kelihatan betul bagaimana Katherine ingin mengikuti sukses serial Bridgerton yang tayang di Netflix. Ia mengambil pola-pola yang diperlihatkan dalam Bridgerton: para pemain pendatang baru yang cantik, ganteng dan segar, gedung-gedung aristokrat nan megah, gaun-gaun mewah dan elegan dan tak lupa sajian musik modern masa kini.
The Buccaneers mengajak kita bertemu dengan tokoh utamanya, Nan St George. Seorang gadis yang selalu berhasil menarik perhatian dengan caranya sendiri tanpa sesungguhnya diinginkannya. Nan bersama gadis-gadis lain, Mabel dan Lizzy Elmsworth, adiknya, Jinny St George dan Honoria Marable. Mereka semua sedang menjadi pendamping pengantin perempuan, sahabat mereka, Conchitta Closson.
Skenario yang dangkal seolah tak memberi ruang eksplorasi bagi gadis-gadis ini untuk saling berebut perhatian. Hanya Nan seorang yang dengan mudah kita rekognisi, juga pertemuannya dengan dua bangsawan Inggris nan ganteng, Duke of Tintagel dan Guy Thwarte. Nafas novel The Buccaneers yang ingin ditiupkan Edith ke dalam karya-karyanya mendadak lenyap tertutupi oleh adaptasi (kelewat) modern ini.
Tapi masih ada ruang bagi kita untuk melihat bagaimana Conchitta bertahan dengan segala kekakuan masyarakat kelas atas Inggris dan menahan gejolak jiwa mudanya yang bebas, liar dan berapi-api. Masih ada ruang-ruang gelap di mana seharusnya kita bisa melihat ruh dari novel The Buccaneers tentang bagaimana fenomena Titled American ini bisa dipandang sinis. Tapi masih bisakah kita berharap dari kreator yang mencoba menyamakan novel Bridgerton yang dipublikasikan di abad 21 dengan novel The Buccaneers yang ditulis oleh penulis yang menjalani kehidupan sebagaimana yang dijalani karakter-karakter dalam novelnya di abad ke-19?
Katherine Jakeways seharusnya belajar dari Martin Scorsese

Sebenarnya bukan hal memalukan apabila kreator ingin mengikuti jejak sukses sebuah serial. Namun pengikut jarang sekali yang meraih sukses melebihi pendahulunya. Dari materi aslinya, Bridgerton tak bisa disamakan dengan The Buccaneers yang lahir dari penulis peraih Pulitzer. Edith menulis novelnya sebagai pengamatan yang jeli sekaligus kritik yang halus atas perubahan yang terjadi dan dialaminya pada masyarakat kelas atas New York di abad ke-19.
Majalah Time sendiri sudah lebih dulu khawatir pada bagaimana sang kreator, Katherine Jakeways, berusaha terlalu besar untuk menjadi epigon dari serial Bridgerton. Dan usaha terlalu besar ini memang menimbulkan frustasi bagi banyak orang terutama bagi mereka yang sempat membaca materi aslinya.
“Yang lebih membuat frustrasi adalah penekanan serial tersebut pada melodramatis romansa yang lazim—pelukan erat pasangan, cemoohan kekasih yang ditolak cintanya, seorang pria yang benar-benar melolong di atas tebing karena menginginkan seseorang yang tidak dapat ia miliki—di atas hubungan yang lebih halus dan rumit.
Di antara gadis-gadis yang merupakan saingan serta saudara perempuan dan teman. Kelembutan antara Nan dan Conchita; ketegangan antara Mabel yang ingin tinggal di Inggris, dan saudara perempuannya, Lizzy yang melarikan diri ke New York setelah mengalami pengalaman traumatis; perang dingin antara Jinny dan Lizzy, yang mengincar orang yang sama—ini adalah beberapa dinamika interpersonal paling menarik yang ditawarkan serial ini.”
Padahal bisa saja Katherine mengambil jalan berliku, sulit dan berani sebagaimana yang dilakukan Martin Scorsese lebih dari 30 tahun lalu. The Buccaneers punya modal untuk menjadi kritik pedas sekaligus drama satir yang menarik. Tapi Katherine sudah mengambil jalannya sendiri, mengubah novel cemerlang menjadi serial drama remaja yang kebetulan saja berlatar waktu di abad ke-19. Tak lebih dari itu. Sayang sekali.